Tepat pagi tadi, aku terbangun dari tidur. Rasa-rasanya aku bertemu Soekarno, beliau bertanya, “anak muda, bagaimana nasib mu, apakah hari ini kau sudah merasakan kemerdekaan yang kami perjuangkan dulu?”
Aku sontak terkejut, “Bung, bukan kah kemarin malam kau sedang di culik oleh golongan muda? Aku lupa, ternyata itu sudah puluhan tahun lalu, mungkin saja situasinya sudah jauh lebih baik, tapi aku ingin katakan andai saja saat itu aku bersama Chaerul Saleh dkk, aku pasti menolak untuk menculik Bung”
Dengan mimpi yang sangat menggangu, aku terbangun. Aku melangkah keluar. Dibawah pohon beringin yang rindang, pagi ini aku duduk termenung sambil melihat tukang kayu memotong bilah demi bilah kayu yang akan di ukir menjadi kursi seharga jutaan (suara)!
Sambil merenungi mimpi tadi malam, aku tertegun dan berfikir. Dihari kemerdekaan ini, apakah demokrasi juga ikut merdeka?
Beriring dengan gempita hari kemerdekaan kali ini, tidak terlepas dari pesta demokrasi yang barusan berlalu dan pilkada yang didepan mata.
Sejenak untuk berkaca pada Pemilu kemarin, menunjukan bahwa efek ekor jas benar terjadi. Hal ini diiringi dengan munculnya paradigma bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif sulit dipisahkan (inheren) dan saling memberikan pengaruh (interdeterminan). Kandidasi Pemilihan Presiden akan memberikan pengaruh berupa efek ekor jas (coat-tail effect) kepada insentif suara partai politik, dimana partai politik yang akan mendapat suara terbanyak adalah partai politik yang mendukung calon Presiden yang menang.
Pada masa Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg), akan memacu mesin partai politik melakukan kampanye yang masif, yang akan memberikan keuntungan ganda baik bagi calon Presiden dan calon Anggota Legislatif atau partai peserta Pemilu.
Pada Pemilu tahun 2024, dapat dilihat bahwa perolehan suara partai politik pengusung Prabowo-Gibran (Pemenang Pilpres) mendapatkan suara yang lebih dominan ketimbang partai politik yang mengusung 2 (dua) calon Presiden lain. Namun di sisi lain, meskipun Prabowo-Gibran sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres, partai pemenang dalam kontestasi Pileg bukan berasal dari partai pengusungnya, melainkan PDI-Perjuangan yang mengusung Ganjar-Mahfud. Hal ini memberikan catatan tersendiri pada konsep efek ekor jas (coat tail effect) yang selama ini ada.
Melihat kecenderungan terjadinya efek ekor jas (coat tail effect) akibat koalisi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengusung calon Presiden ini, tentunya tidak terlepas dari preferensi apa yang dijadikan dasar oleh partai politik dalam mengusung calon? Apakah partai politik masih mendasarkan preferensinya pada basis ideologi kepartaian dalam mengusung calon? Apakah preferensi itu akan tetap sama untuk mengusung calon dalam kontestasi Pilkada berikutnya?
Pada masa pra-proklamasi (1945-1949), partai politik memiliki esensi yang kental secara ideologis, bahwa partai politik di dirikan dengan basis ideologi yang dimiliki dan berkembang di tubuh anggota partainya. Meskipun dengan dikeluarkanya Maklumat tanggal 3 November 1945 atas dasar usulan BP KNIP, pada masa itu dengan tegas Pemerintah mengatakan bahwa Pemerintah menyukai berdirinya partai politik sebagai suatu persiapan pemilihan umum pada Januari 1946 (meskipun tidak jadi terlaksana). Dimana pada masa itulah timbul dan berdirinya sepuluh partai politik yang salah satunya adalah Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) 7 November 1945 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 7 November 1945.
Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), yang dikenal juga dengan istilah pemerintahan parlementer, juga di tandai dengan kuatnya ideologi partai politik yang dengan kekuasaan “Mosi Tidak Percaya” nya, berhasil menjatuhkan 7 kabinet dalam masa pemerintahan 9 tahun (mulai dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Juanda). Lahirnya partai politik di akibatkan dari kuatnya ikatan ideologi partai politik dibagi oleh Herbet Feith berdasarkan corak partai politik kedalam 5 aliran besar yaitu: Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis dan Komunisme. Yang pada hakikatnya menunjukan pertentangan ideologi antara Islam-Tradisionalisme Jawa dengan Komunis-Sekuler. Dan bahkan Pemerintah melalui Kementrian Penerangan membagi partai tersebut kedalam empat klasifikasi, yaitu: dasar ketuhanan, dasar kebangsaan, dasar marxisme dan partai lain-lain.
Pada fase ini dapat menggambarkan lebih jelas gradasi ideologi adalah ketika di dalam konstituante yang akan merumuskan kembali UUD bagi negara Indonesia, pertentangan antara golongan Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam kembali muncul dan memanas, dimana keduanya saling memperjuangakan ideologinya untuk menjadi dasar idelogi bangsa Indonesia, hal inilah yang membuat konstituante mandek dan akibatnya Soekarno dalam pidatonya tanggal 28 Oktober 1956 meminta agar partai-partai dibubarkan saja. Dan kemudian atas dasar itu juga Soekarno mengeluarkan Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.
Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), partai politik banyak yang dibubarkan oleh Soekarno melalui Penpres 1959, yang dimana Soekarno mengatakan bukanlah diktatorisme melainkan demokrasi, tinggalah kekuatan yang sangat dominan pada masa itu adalah Presiden, PKI dan TNI-AD. Sedangkan partai-partai lain dengan ideologi keagamaan termarginalisasi dan hanya menjadi pajangan saja. Dengan kuatnya PKI pada masa itu, partai lain menjadi redup, namun setelah kejadian G 30 S, PKI mengalami keruntuhan dan tinggalah kekuatan yang tersisa, TNI-AD.
Pada masa orde baru (1966-1998), terjadi pergeseran kekuatan politik dan politisi dari sipil ke militer. Yang mulanya pada 1971 terdapat 9 partai politik peserta pemilu dan kemudian terjadi fusi partai politik melalui UU No. 3 tahun 1973, sehingga pada tahun 1977 sampai 1998 partai politik menjadi tiga, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (gabungan NU, Permusi, PSI, Perti), Partai Demokrasi Indonesia (gabungan PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan PKI) dan Golongan Karya.
Klasifikasi yang dilakukan Soeharto masih dapat dikatakan berdasarkan ikatan ideologi. Meskipun pada waktu itu terjadi emaskulasi partai, Golkar menjadi kuat dengan bebagai fasilitas, dan tampil sebagai partai hegemonik, dan partai lain hanya menjadi partai kelas dua atau lincenced parties.
Hal tersebut menggambarkan bahwa ideologi yang jelas dalam setiap partai akan memberikan dampak kuatnya sikap politik dari partai politik, yang pada ujungnya mencapai hal yang paling fundamental adalah sikap saling mengawasi dan saling oposisi, guna menjadi penyeimbang dalam konteks pemerintahan.
Sedangkan pada era reformasi ini, partai politik seperti telah melepaskan dirinya dari cengkraman ideologinya. Krisis identitas yang timbul di tengah-tengah tubuh partai sebagai akibat dari sikap partai yang menjadi pragmatis dan tidak ideologis. Partai politik lebih cenderung menjadi partai yang berebut kursi dan jabatan tanpa pernah memberikan tawaran pemikiran alternatif yang diproduksi dari ideologi masing-masing partai. Fenomena ini dikatakan Giovani Sartoni sebagai kecenderungan sentrifugal yang mengakibatkan ideologi mengarah ketengah (depolarisasi ideologi).
Pada masa sekarang ini, depolarisasi partai politik menjadi sangat terang. Tidak ada pemerintahan yang ideologis, tidak ada partai yang dengan kental menyuarakan ideologinya, tidak ada dialektika ideologi antar partai. Bahkan yang paling mengenaskan adalah, basis ideologi yang pada masa pra-proklamasi sampai orde baru jelas-jelas bersebrangan malah menjadi satu koalisi. Dengan dalih, untuk kepentingan rakyat banyak, toleransi dan kebebasan kehendak untuk menentukan sikap politik, menjadikan penelanjangan diri akan ideologi partai menjadi pembenaran.
Partai politik tercerai berai, berlomba-lomba merapat ke pemenang kontestasi dengan tanpa sadar atau bahkan sadar meninggalkan basis ideologinya. Atau bahkan, meninggalkan basis koalisinya yang sebelumnya di bangun dengan argumen-argumen ideologis sebagai landasan sikap politik. Terlebih lagi, partai yang menjadi pengusung utama kandidat presiden yang bersebrangan malah dengan terang-terangan menyatakan akan bergabung dengan pemenang pemilu, padahal partai inilah yang mendapatkan efek ekor jas (coat-tail effect) terbesar akibat sikap politiknya yang bersebrangan.
Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial dikenal bentuk oposisi, yang merupakan salah satu kristalisasi dari konsep trias polica dan merupakan suatu bentuk check and balances, parlemen merupakan penjelmaan rakyat untuk mengawasi (oposisi) jalanya pemerintahan. Konsekuensinya, parlemen tidak boleh terkontaminasi (berkoalisi) oleh pemerintah atau dalam kata lain tidak boleh ada satupun partai di parlemen yang menyatakan sikap politiknya ‘satu gerbong’ dengan pemerintah.
Lalu, bagaimana dengan saat ini, jika sebahagian besar partai politik diparlemen berlomba-lomba masuk ke gerbong pemerintahan? Siapa yang akan menjalankan fungsi esensial (pengawasan) di parlemen?
Tidak terlepas dari itu, partai politik yang seharusnya memiliki garis komando yang linear ke bawah, malah menunjukan berbagai perpecahan preferensi dalam mengusung (koalisi) calon kepala daerah. Hal ini terlihat dari berbagai koalisi pencalonan di daerah yang relatif tidak linear dengan koalisi pada Pilpres dan Pileg kemarin.
Tentunya hal ini tidak hanya menggambarkan lunturnya ideologi partai politik, namun hal ini juga dapat menimbulkan keadaan berbahaya bagi kondisi ketatanegaraan dan demokrasi, dimana jika seluruh partai politik cenderung bersikap pragmatis, akan memberikan dampak negative-destruktif
Hari ini, partai politik sebagai tonggak dialektika sangat diperlukan. Bahkan, dalam konteks filsafat kuno, Yin dan Yang adalah dua komponen berbeda yang harus ada dalam satu kondisi (sine qua non), dan dalam konteks ber-agamapun keberadaan iblis juga di ‘biarkan’ oleh Tuhan untuk menjadi kecenderungan penyeimbang manusia, dan dalam konteks filsafat Pancasila oposisi menjadi kebutuhan dalam pemerintahan yang merupakan konsekuensi yuridis dari adanya sila ke-empat Pancasila yang memberikan wadah penyelesaian pertikaian antara koalisi dan oposisi.
Jika hal ini tetap dibiarkan, penulis memiliki hipotesis lunturnya ideologi dan menonjolnya sikap pragmatisme partai politik akan membawa negara dan bangsa ini ke arah destruktif tanpa adanya dialektika penyeimbang pemerintah.
Lalu, dengan kondisi begini apakah demokrasi kita sudah merdeka?
Penulis:
Satriansyah Den Retno Wardana, S.H., M.H., CPM
Peneliti/Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
Kelahiran Kota Pematangsiantar,
Juara II Nasional Penulisan Blog Konstitusi dan Anti Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
Juara I Nasional Resensi Buku Komisi Yudisial RI
Panelis Termuda pada Call for Paper Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Istana Negara Jakarta















































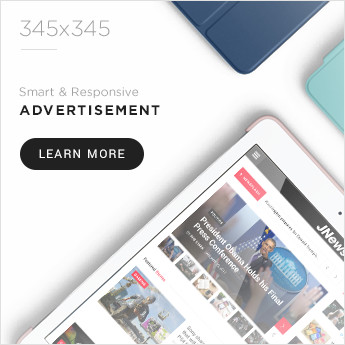

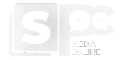
Discussion about this post