Sudah menjadi suatu Notoire Fetin, jika pemilu ataupun pilkada dianggap sebagai pengejawantahan dari demokrasi. Meskipun demikian, apakah hipotesa tersebut benar? Atau setidaknya apakah hipotesa tersebut relatif benar dalam konteks Indonesia?
Maka dalam rangka mengisi premis-premis tersebut, diperlukan suatu diskursus untuk melihat bagaimana kontelasi pemilu ataupun pilkada dalam demokrasi di Indonesia.
Dalam melihat bagaimana arah demokrasi Indonesia terdapat ucapan founding father Soekarno yang dapat menjadi awal dari pembahasan kali ini, pada 1 Juni 1945 Soekarno pernah mengatakan bahwa:
“Negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup…”
Prinsip pemerintahan yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin kesetaraan warga negara dengan menghormati hak minoritas (majority rule, minority rights) dengan tetap mendasarkan pada kedaulatan rakyat yang berlandaskan kekeluargaan. Cita kedaulatan rakyat yang berlandaskan kekeluargaan menumbuhkan ruang multikulturalisme yang hidup dan berkembang di Indonesia sebagai sistesa dari pengalaman pahit kolonial. Maka pengakuan terhadap hak budaya suatu etnis tertentu yang notabene minoritas menjadi hal yang penting. Hal ini dapat dipahami dengan memandang bahwa individu sebagai subjek hukum tidak bisa dilepaskan dari akar sosialnya.[1]
Cita persaudaraan dan kesamaan kedudukan telah mengakar kuat dalam pergaulan bangsa Indonesia. Persilangan antar budaya telah lama diterima sebagau suatu kewajaran yang hidup ditengah-tengah penduduk kepulauan Nusantara. Yang menjadi elemen penting adalah bagaimana tradisi musyawarah tumbuh dalam masyarakat desa di Nusantara, yang jika dilihat secara aktual nilai-nilai tersebut masih tumbuh dan berkembang di berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan pandangan yang dimana nilai-nilai demokrasi mengakar kuat di negara Indonesia, Bung Hatta pernah memaparkan konsep demokrasi, yakni:[2]
“Negara haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Tetapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan di propagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.”
Dalam perjalanannya konstruksi demokrasi Indonesia yang digali dari nilai-nilai yang berkembang di bumi nusantara memiliki sumber nilai yang otentik.
M Hatta memaparkan bahwa setidaknya sumber nilai yang menjadi penyanggah cita demokrasi di Indonesia terdapat tiga elemen penting, yakni Pertama, stimulus desa melalui tradisi kolektif dan musyawarah Kedua, nilai Islam yang diserap dari nilai keadilan dan kebenaran. Ketiga, ideologi Barat yang memberikan stimulus pada aspek kemanusiaan.[3]
Stimulus Tradisi Kolektif
Stimulus pertama yang dilihat melalui perspektif nilai-nilai di desa dapat dilihat bahwa konsep demokrasi merupakan suatu konsep baru yang muncul pada fase kemerdekaan di Indonesia. Jika dilihat lebih jauh, raja autocrat sebagai penguasa kerajaan-kerajaan dalam sejarah Indonesia merupakan bentuk tersendiri dari sistem yang sudah mengakar lama di nusantara. Meskipun demikian, jika dilihat dari unit politik kecil seperti nagari di Sumatera Barat, desa di Jawa, dan banjar di Bali akan terlihat bahwa nilai demokrasi juga hidup di masyarakat tersebut.
Bahkan Tan Malaka sendiri berpandangan bahwa kedaulatan rakyat telah menjadi paham sejak adanya nusantara. Misalnya di Minangkabau pada abad 14 hingga 16 kekuasaan raja harus mengacu pada batas-batas keadilan dan kepatutan. Di Minangkabau esensi raja dijawantahkan melalui alur logika dan juga keadilan. Alur inilah yang menjadi titik tolak keputusan raja akan diterima atau ditolak ketika bertentangan dengan prinsip keadilan atau akal sehat. Hal ini dapat dilihat melalui istilah Minangkabau yakni, “Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat beraja pada alur dan patur”.[4]
Hatta berpandangan bahwa nilai demokrasi tetap dapat tumbuh dan bertahan di nusantara meskipun dibalik bayang-bayang kerajaan yang sangat feudal dipengaruhi oleh faktor produksi penting yang dimiliki oleh desa maupun masyarakat secara kolektif, tidak dikuasai oleh raja. Dengan adanya kepemilikan kolegial ini maka dalam menjalankan kegiatannya mengharuskan adanya musyawarah mufakat. Hal ini yang menjadi salah satu embrio munculnya musyawarah dan tradisi gotong royong antar masyarakat. Yang kemudian tradisi masyarakat ini melahirkan konsep rapat dalam tradisi musyawarah-mufakat dibawah kepemimpinan desa setempat, hingga muncullah sebuah istilah Minangkabau “Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” yang artinya bulat air karna pembuluh/bambu, bulat kata karna mufakat.[5]
Elemen lain yang membentuk demokrasi di desa adalah adanya hak bagi masyarakat desa untuk melakukan protes atas peraturan desa dengan cara berkumpul di alun-alun tanpa melakukan kegiatan apapun yang mana cara ini dilakukan untuk menunjukan sikap demokrasi yang damai. Selain itu, masyarakat juga dimungkinkan untuk melaksanakan hak nya melalui keputusan untuk menyingkir dari kekuasaan raja sebagai hak dari sesorang yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Anasir-anasir ini lah yang menjadi analisis dan bahan pertimbangan bagi pendiri bangsa dalam merumuskan konsep demokrasi Indonesia yang modern dari nilai-nilai demokrasi desa. Hatta kembali menjelaskan bahwa elemen rapat, mufakat, gotong royong, hak protes dan hak menyingkir menjadi pokok penyanggah bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar demokrasi Indonesia modern.[6]
Stimulus Islam
Stimulus kedua melalui perspektif Islam dalam memberikan konstruksi kepada demokrasi di Indonesia dapat dilihat melalui pandangan Hatta bahwa stimulus Islam merupakan sumber yang menghidupkan cita demokrasi sosial bagi pemimpin pergerakan. Selain itu Soekarno juga menyampaikan hal yang senada dimana pengaruh Islam membawa tranformasi masyarakat yang feodal kepada masyarakat yang demokratis di Indonesia.[7]
Nilai keyakinan atau tauhid di dalam tubuh Islam memberikan sumbangsih terhadap tumbuhnya nilai demokrasi di Indonesia. Keteladanan hidup Nabi Muhammad menjadi titik pangkal untuk melakukan pengaturan kehidupan manusia yang egaliter. Pengaturan hidup manusia yang memberikan kekuasaan mutlak pada sesame manusia tidak adil. Oleh karenanya sikap memasrahkan diri kepada Tuhan mengkehendaki tatanan sosial yang lebih egaliter dan demokratis.[8] Ketauhidan secara esensial memberikan makna kesederajatan di hadapan Tuhan yang juga meninggikan harkat dan martabat manusia. Bahwa dalam perjalananya, utusan Tuhan sekalipun tidak dapat memaksakan kebenaran di tengah-tengah masyarakat, dimana Nabi dan Rasul hanya untuk menyampaikan kebenaran (tabligh dan balagh). Dengan adanya prinsip egaliter tersebut, Islam mengajarkan untuk menjalin kerjasama dan persaudaraan sesame umat manusia di dalam wadah sosial dan persaudaraan.[9]
Dalam makalahnya, Nurcholis Madjid mengutip pendapat Robert N. Bellah seorang Sosiolog Amerika nasionalisme modern tampak pada sistem masyarakat Madinah masa nabi dan para khalifah. Sistem yang dibangun nabi pada masa itu merupakan bangunan komunitas nasional modern yang lebih dari sekedar apa yang di bayangkan (a better model for modern national community building than might be imaginad). Serta sistem pemerintahan Madina pada masa itu disebut sebagai sistem yang egaliter partisipatif (equalitarian participant nationalism) dimana sistem ini sangat inklusif bagi setiap masyarakat yang ingin memberikan partisipasi berdasarkan kemampuan setiap orang dimana tidak ada sistem yang menuju kepada pengundusan dan eksklusivisme suku atau kelompok.[10]
Kehadiran nilai-nilai Islam di tengah masyarakat nusantara pada masa itu merubah pandangan dunia dan etos masyarakat yang mengarah kepada konsep kesetaraan antar manusia dan konsep nafs yang mengarah kepada tanggungjawab individu. Aspek Islam dalam kehidupan masyarakat nusantara merubah sistem yang sebelumnya sangat feodalistis menjadi egaliter yang terlihat dalam kehidupan masyarakat Melayu dimana sebelumnya terdapat pribahasa “Melayu pantang membantah” yang berubah menjadi “raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah”.[11] Yang mana hal ini sangat kentara pada masa itu, dimana yang sebelumya konsep kepatuhan menjadi paku mati, berubah menjadi suatu konsepsi yang menimbulkan konsekuensi etis bagi setiap perbuatan penguasa.
Stimulus Demokrasi Barat
Stimulus ketiga yang disumbang oleh pemahaman demokrasi barat di nusantara dapat dilihat bahwa intervensi budaya, sosial dan ekonomi nusantara memiliki catatan waktu dan sejarah yang cukup panjang dari masyarakat Eropa. Pada fase yang paling dekat perkembangan ideologi Barat diserap melalui aktivis Perhimpunan Indonesia (PI) yang berfokus pada ide sosio-demokrasi (social democracy) yang secara gramatikal harus dipahami bahwa ide tersebut menjadi suatu konsepsi di Indonesia berupa konsep sosdem bukan konseo demokrasi sosial.[12]
Berbagai sumbangsih tersebut pada akhirnya bermuara pada suatu pergulatan intelektual yang konkret dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi. Muhammad Yamin pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 pertama kali menyampaikan perihal gagasan kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan (permusyawaratan). Konsep kedaulatan rakyat dan musyawarah sebagai dasar negara juga disampaikan oleh Woerjaningrat dimana konsep kemerdekaan Indonesia harus bersendi kekeluargaan. Selanjutnya pada 31 Mei 1945 Soepomo menyampaikan pentingnya permusyawaratan dengan memaparkan tiga teori pemikiran yang dapat dianalisis dalam konteks keindonesiaan yakni, a) teori individualistis yang diajarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke dimana negara sebagai masyarakat hukum (legal society) dibangun berdasarkan kesepakatan seluruh pihak (contract social), b) aliran pemikiran golongan negara dimana negara sebagai suatu golongan (klasse) yang menindas klasse lain, c) selanjutnya yakni teori itegralistik dimana negara tidak menjamin kepentingan sesorang atau golongan tetapi preferensi mengarah kepada persatuan dan kepentingan seluruh masyarakat. Dan pada akhirnya Soepomo berkesimpulan bahwa aliran ketiga dimana teori integralistik menjadi jalan ideal bagi bangsa Indonesia.[13]
Selanjutnya pandangan Soekarno dalam pidatonya pada Rapat Besar 1 Juni 1945 tentang dasar falsafah negara Indonesia (philosofische gronslag) yang memasukan prinsip mufakat dan demokrasi melalui pertanyaan retoris yang menjadi ciri khas Bung Karno, dengan menyatakan jawaban bahwa dasar falsafah Indonesia merdeka adalah mufakat dan permusyawaratan sebagai suatu sistem negara “semua untuk semua”, semua untuk satu dan satu untuk semua dengan bingkai perwakilan. Permusyawaratan menurut Soekarno hendak menguatkan persatuan dimana melalui badan permusywaratan menjadi wadah konfrontasi aspirasi tiap golongan dalam masyarakat. Dan permusyawaratan menjadi suatu pembimbing dengan semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam mencapai suatu sintesa kebaikan bagi masyarakat.
Selama masa reses persidangan BPUPK pada 2 Juni sampai 9 Juli, Panitia Kecil mengumpulkan usulan 40 anggota Chuo Sangi In (lin) yang mana terkait demokrasi setidaknya diusulkan 12 lin, bentuk kesatuan 17 lin dan federasi oleh 2 lin serta konfederasi oleh 1 lin. Persoalan structural lainnya tidak terlepas dari pembahasan dimana 3 lin mempertahankan Tyuuoo Sangi In, sedangkan 5 lin minta untuk ditambah beberapa orang lagi. 18 lin sebagai suara mayoritas mengusulkan badan parlemen yang baru. Sedangkan terkait bentuk pemerintahan terdapat 11 lin yang mengusulkan republic dan selebihnya mengusulkan jenis negara monarki. Terkait wujud kepala negara terdapat 10 lin mengusulkan agar dipimpin oleh direktorium, 5 orang mengusulkan presiden dan selebihnya mengusulkan pilihan lainnya.[14] Hal ini menunjukan bahwa dalam perumusan Kemerdekaan Indonesia sendiri tidak terlepas dari berbagai konstelasi pemikiran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Pada masa persidangan kedua BPUPK tanggal 10 Juli sampai 17 Juli pembahasan terkait demokrasi dalam konsepsi permusyawaratan sebagai jalan untuk implementasi kedaulatan rakyat menjadi topik yang krusial. Pada mulanya Bung Karno menyampaikan usulan Panitia Kecil terkusus masalah Bentuk Negara yang notabene tidak memunculkan banyak perdebatan. Agoes Salim menyampaikan juga bahwa tidak ada yang menginginkan konsep provincialism atau separatism maka uni dan federasi bukan isu penting. Yang menjadi isu penting adalah bagaimana konsepsi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Positif Konstruktif
Yang menjadi isu penting dari konsep berdemokrasi lainnya adalah persoalan “mufakat” yang tentunya tidak tendensius kepada jumlah dan kuantitas belaka sebagaimana kelompok barat melainkan pada klusifisme dalam mengakomodir apsirasi dan pandangan minoritas dalam mengambil keputusan, sebagaimana pandangan pada Rapat Besar 11 Juli 1945 yang disampaikan oleh Agoes Salim. Yang selanjutnya isu esensial berbentuk semangat musyawarah-mufakat yang akan memberikan kontribusi ideal kepada perumusan isu ketatanegaraan Indonesia dalam Rancangan Undang Undang Dasar.
Demokrasi musyawarah-mufakat tentunya sejalan dengan pemikiran politik Indonesia saat itu yang menganut konsep kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yakni, “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi senegnap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Yang pada intinya ingin mengkonstruksikan suatu pemerintahan yang dapat menjadi wadah yang mengatasi perbedaan paham perseorangan dan golongan. Yang pada akhirnya demokrasi dengan semangat kekeluragaan menjadi suatu prinsip ideal yang diberlakukan secara nasional. Pada level kesadaran diskursif soal kesepakatan bahwa aspek demokrasi harus menjadi elemen dan mengambil bagian pada bidang sosial, ekonomi dan politik serta diberbagai aspek lainnya.[15]
Dalam pandangan yang lebih mendalam melalui alur-alur pemikiran Pancasila, gagasan demokrasi permusyawaratan yang didasari pada prinsip Pancasila merupakan suatu upaya dalam “making democracy work”, yang mana demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah “Demokrasi Indonesia” yang mengakomodir nash kepribadian Indonesia.[16] Demokrasi di Indonesia bukan suatu alat teknis melainkan cerminan jiwa, kepribadian dan suatu tujuan nasional.[17]
Pandangan Soekarno menggambarkan hal tersebut bila mana demokrasi hanya digunakan sebagai alat belaka maka tidak berbeda jauh dengan fasisme maupun proletariat yang digunakan hanya sekadar alat mencapat wujud masyarakat yang ideal. Soekarno yang juga merujuk pada pandangan Karl Steurman manyatakan bahwa demokrasi atau parlementaire democratie merupakan ideologi pada sejarak periode saja yang merupakan ideologi politik kapitalisme yang diatas (Kapitalismus in Aufsteig) sedangkan fasisme adalah ideologi kapitalisme dibawah (Kapitalismeus in Neidergang) yang digunakan untuk menyelamatkan kapitalisme. Soekarno juga menyatakan bahwa:
“…kedaulatan rakyat bukan sekadar alat saja. Kita berfikir dan berasa bukan sekadar teknis, tetapi kejiwaan, psikoogis nasional dan kekeluargaan, Dalam alam fikiran dan perasaan demokrasi bukan sekadar teknis saja, tetapi satu geloof, kepercayaan…”
Penjabaran sila keempat Pancasila memberikan ciri pemikiran demokrasi di Indonesia yang dijawantahkan dalam pokok pemikiran ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Petama, kedaulatan “kerakyatan”, yang menjadi cerminan semangat anti penindasan yang ditimbulkan feodalisme dan kolonialisme yang kemudian mengingnkan sintesa egalitarianism. Kedua, kedaulatan “permusyawaratan”, yang dalam mengatasi berbagai perbedaan faham dan pandangan dilakukan dengan syarat mutlak yakni permusyawaratan perwakilan dengan mendasarkan pada asa kerakyatan dalam menjalankan setiap hukum dan pemerintahan. Selain itu demokrasi Indonesia juga mengandung ciri “hikmat-kebijaksanaan”, yang merefleksikan etis sebagaimana Mohammad Hatta berpandangan bahwa kerakyatan di Indonesia bukan persoalan suara terbanyak namun dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, hal ini memberikan makna bahwa demokrasi Indonesia berkaitan secara menyeluruh dengan seluruh sila Pancasilanya.[18]
Dalam konteks demokrasi permusyawaratan untuk melihat dan menilai suatu keputusan politik setidaknya didasari pada empat prasyarat yakni a) adanya rasionalitas dan keadilan, b) mementingkan kehendak banyak orang, c) memiliki orientasi visioner yang jauh kedepan, dan d) bersifat imparsial dengan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif.[19] Tentang bagaimana cara demokrasi permusyawaratan bekerja Hatta menekankan pentingnya tradisi demokrasi desa namun dengan berbagai pertimbangan apabila ingin menerapkannya di tingkat negara. Mufakat di desa diambil dengan keputusan yang mengutamakan sepakat sedangkan pada tingkat negara tentunya berbagai pandangan ideologis partai dan dialektika politik akan sulit menyentuh titik sepakat dan keputusan mufakat.
Dengan berbagai kondisi yang kompleks tersebut sebagai jalan keluar harus dimungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Hal ini dikarenakan mufakat yang dipaksanakan sebagaimana dinegara totaliter tidak sesuai demokrasi di Indonesia. Dengan tidak ada musyawarat tiap orang berhak menyatakan pendapat dan tidak ada mufakat.[20] Demokrasi permusyawaratan pada akhirnya akan mengakomodir suara mayoritas yang diterima sebagai prayarat minimum dari demokrasi yang tentunya tidak meninggalkan aspek subsntatif dan iklusifitas dari partisipasi masyarakat. Atas dasar itu pemungutan suara ataupun voting ditempatkan sebagai pilihan terakhir yang tentunya tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan etis saling menghormati. Maka dari itu, relatif relevan jika dikatakan bahwa sistem pegambilan keputusan dengan suara terbanyak (voting) sebagai salah satu jalan demokrasi merupakan antitesa dari kondisi quo Indonesia yang sesungguhnya condong kepada demokrasi kualitatif bukan demokrasi kuantitatif.
Pemilu Usai, Pilkada Berderai!
Penulis adalah
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Pematangsiantar 2018-2020
Ketua Umum Komunitas Penulis Hukum FH UMSU 2019-2020
Koordinator Presidium HAN/HTN Bersatu FH UMSU 2019-2020.















































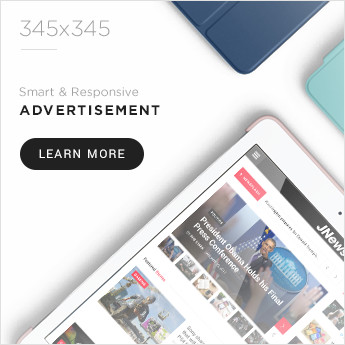

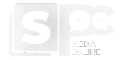
Discussion about this post